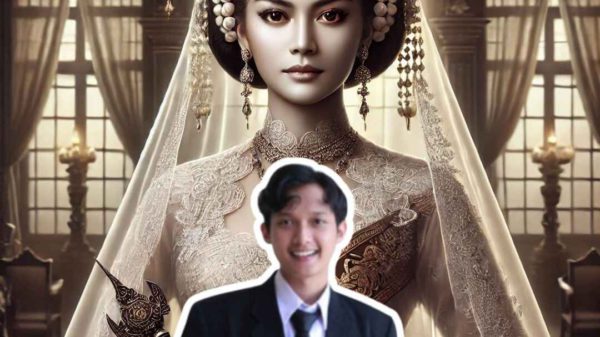KUNINGAN (MASS) – Bagi masyarakat Indonesia yang pernah melihat perpolitikan tanah air menjelang pesta demokrasi sebelum tahun 1998, pasti bisa merasakan perbedaannya dengan saat ini. Pasti banyak parameter kalau kita ingin melihat secara komprehensif seperti dalam Teori Perbandingan Politik baik yang dikemukakan oleh Eugene Miler, David Hume, Henri Saint-Simon, Aguste Comte, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan ini mari kita buka fenomena empirik yang mudah dilihat saja.
Sebelum 1998 saat pesta demokrasi memasuki fase kampanye meriahnya luar biasa, konvoi kendaraan bermotor baik roda empat ataupun roda dua sangat menghiasi jalanan hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa di berbagai ruas jalan di kota-kota. Metode pengumpulan masa di lapang-lapang terbuka dilakukan untuk menunjukan kekuatan, bahkan tidak sedikit artis-artis dihadirkan sebagai vote getter.
Untuk semua ini tentu dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fenomena ini melahirkan satu pemikiran, bagaimana agar pesta demokrasi tetap berlangsung sesuai aturan main tetapi dengan biaya yang efisien ? Sebab banyak orang yang meyakini sistem demokrasi berbiaya tinggi inilah yang menimbulkan kecenderungan orang untuk melakukan tindakan koruptif sebagai kompensasi atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat kampanye.
Seiring dengan waktu dan kedewasaan berpolitik masyarakat, akhirnya mulai terjadi pergeseran paradigma. Kampanye tidak lagi harus dilakukan dengan model konvoi di jalanan dan pengerahan ribuan masa, karena (1) biayanya pasti mahal, (2) yang hadir belum tentu juga milih dia, (3) model seperti itu dinilai sudah tidak simpatik karena mengganggu kepentingan yang lain. Di sini nalar kedewasaan berfikir sudah mulai berkembang, meskipun tentu belum semua lapisan masyarakat bisa berfikir seperti ini.
Transformasi politik mulai bergeser dengan model-model simpatik. Blusukan ke tempat-tempat yang dinilai kotor misalnya, menyuapi nenek-nenek, menggendong anak kecil, dan lain-lain. Kampanye simpatik ini banyak dilakukan dalam menarik simpati warga, dan tentu sah-sah saja. Apalagi kalau hal-hal baik itu bisa dilakukan secara konsisten.
Masyarakat jangan hanya melihat calon saat masa kampanye saja. Lebih dari itu lihatlah perilakunya justru saat telah terpilih. Apakah ia masih selalu dekat dengan rakyat ? Apakah ia masih mau menyuapi nenek-nenek ? apakah ia masih mauberkunjung ke tempat-tempat yang mungkin dinilai kotor ? Coba perhatikan berbagai spanduk dan poster, banyak sekali gambar-gambar yang sangat simpatik dan menyentuh hati. Sekali lagi mudah-mudahan masih bisa konsisten setelah ia terpilih nanti.
Sebab lebih jauh dari itu sebagai umat beragama pasti menyadari, bahwa jadi pemimpin itu tidak mudah. Jabatan pemimpin itu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Di satu sisi kita patut bangga karena betapa banyaknya orang yang ingin memikul amanah yang besar itu.
Mungkin ada sebagian kecil yang tidak mau jadi pemimpin. Bukan tidak bisa, tetapi khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di Mahkamah Rabbi nanti. Mempertanggungjawabkan diri sendiri saja tentu tidak mudah, apalagi untuk mempertanggungjawabkan seluruh rakyat yang diwakilinya. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan di Indonesia ini lahir para pemimpin dan para wakil rakyat yang amanah terhadap bangsa dan negaranya.***
Penulis: Dede Farhan Aulawi (Pengamat Politik)