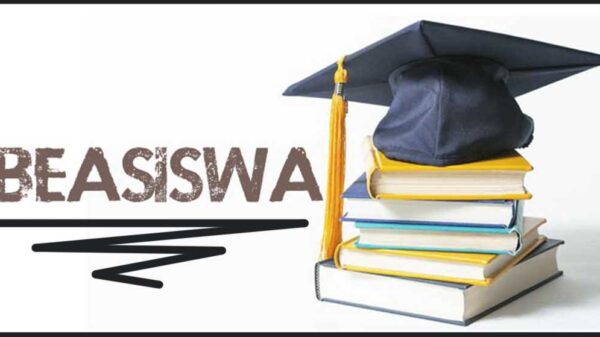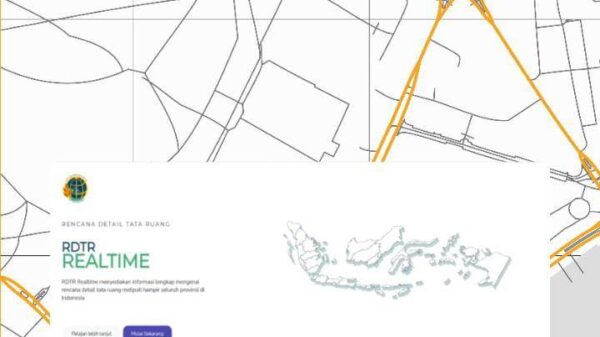“Di Berita: rakyat kita paling bahagia
Di Rumah: Bu, buku tulisku habis
Lalu ia mengambil tali, tepat saat negara sibuk memoles citra diri”
Potongan narasi di atas bukan sekadar puisi getir; ia adalah diagnosis sosial. Di satu sisi, negara baik pusat maupun daerah sibuk memproduksi klaim kebahagiaan kolektif melalui statistik, indeks, dan slogan. Di sisi lain, realitas mikro di ruang keluarga menunjukkan paradoks yang telanjang: kebutuhan paling elementer pendidikan bahkan tak terjangkau. Di antara jurang itulah, kebijakan publik kehilangan makna kemanusiaannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara tampak terlampau fokus pada kebijakan populis simbolik, salah satunya melalui program makan bergizi (MBG). Secara normatif, MBG adalah kebijakan yang terdengar luhur: gizi anak, masa depan bangsa, investasi manusia. Namun problemnya bukan pada niat, melainkan pada logika prioritas dan cara negara memaknai kesejahteraan.
Negara seolah mengira bahwa kenyang adalah satu-satunya syarat hidup layak, seakan manusia hanya tubuh biologis yang cukup diberi asupan kalori. Padahal pendidikan yang direpresentasikan secara getir oleh “buku tulis yang habis” adalah fondasi kesadaran, daya kritis, dan mobilitas sosial. Ketika negara lebih sibuk mengurus apa yang masuk ke mulut anak, tetapi abai pada apa yang mengisi kepalanya, maka yang lahir bukan manusia merdeka, melainkan generasi yang sekadar bertahan hidup.
Lebih problematik lagi, pemerintah daerah seringkali hanya menjadi operator administratif, bukan aktor kritis yang membaca konteks lokal. Mereka berlomba menyukseskan program pusat demi laporan kinerja, sambil menutup mata pada kenyataan bahwa sekolah-sekolah kekurangan alat tulis, ruang kelas rusak, guru honorer dibayar tak layak, dan anak-anak dipaksa beradaptasi dengan kurikulum yang tak berpijak pada realitas sosialnya. Di sini, kebijakan pusat yang seragam bertemu dengan ketiadaan keberanian daerah, menghasilkan kegagalan yang sistemik.
Narasi “rakyat paling bahagia” yang terus diulang melalui media dan konferensi pers justru menjadi bentuk kekerasan simbolik. Ia meniadakan penderitaan nyata dengan angka-angka abstrak. Kebahagiaan direduksi menjadi variabel statistik, bukan pengalaman hidup. Ketika negara berkata rakyat bahagia, sementara rakyat bertanya apakah mereka mampu membeli buku tulis besok pagi, maka yang terjadi bukan optimisme, melainkan pengkhianatan makna kebahagiaan itu sendiri.
Kalimat terakhir “lalu ia mengambil tali” harus dibaca sebagai teriakan putus asa struktural, bukan tragedi individual. Ia adalah hasil akumulasi kebijakan yang lebih peduli citra daripada substansi, lebih sibuk memoles wajah ketimbang membenahi tulang punggung masyarakat. Dalam perspektif kritis, ini adalah konsekuensi dari negara yang gagal hadir secara utuh: hadir memberi makan, tetapi absen memberi harapan.
Negara yang sehat bukan negara yang sekadar memastikan warganya tidak lapar, melainkan negara yang menjamin martabat hidup: pendidikan yang layak, akses yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada realitas, bukan sekadar panggung politik. Jika tidak, maka MBG dan berbagai program sejenis hanya akan menjadi alat kosmetik kekuasaan mengenyangkan perut, tetapi membiarkan pikiran tetap lapar, dan masa depan tetap rapuh.
Oleh: Fillah Ahmad Abadi
Mahasiswa Kuningan