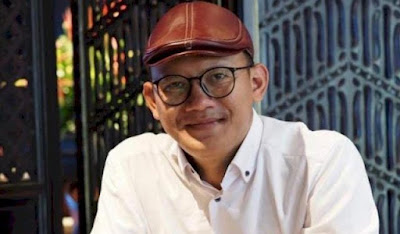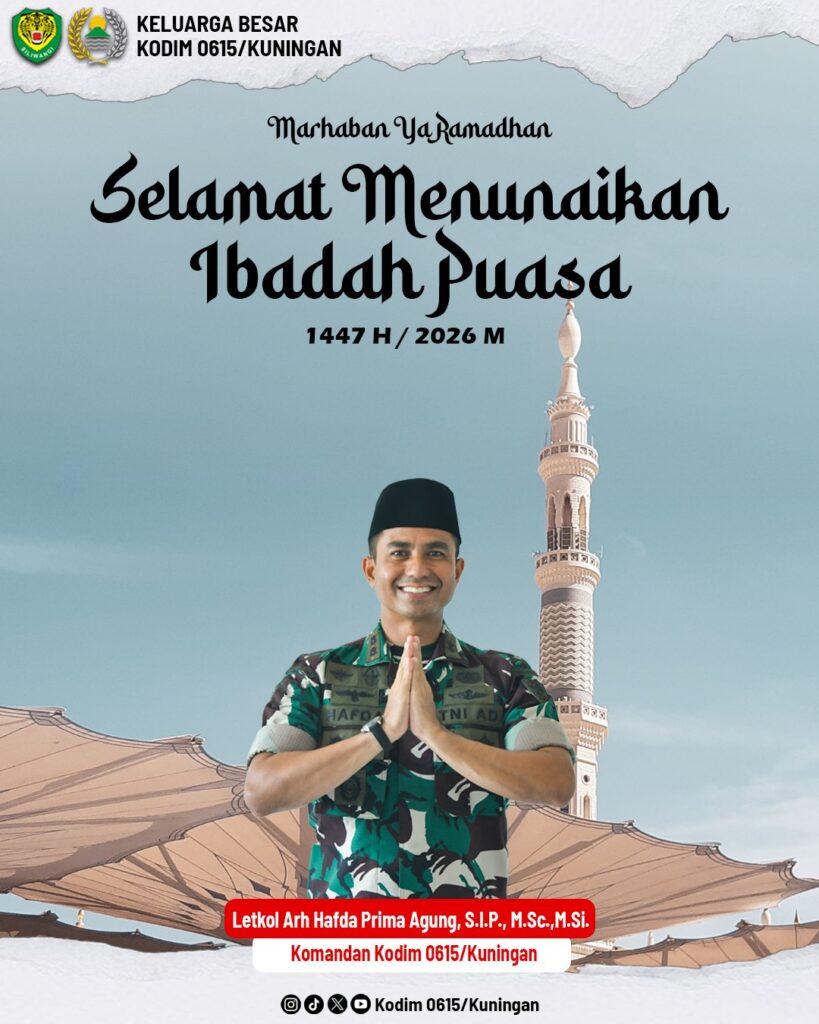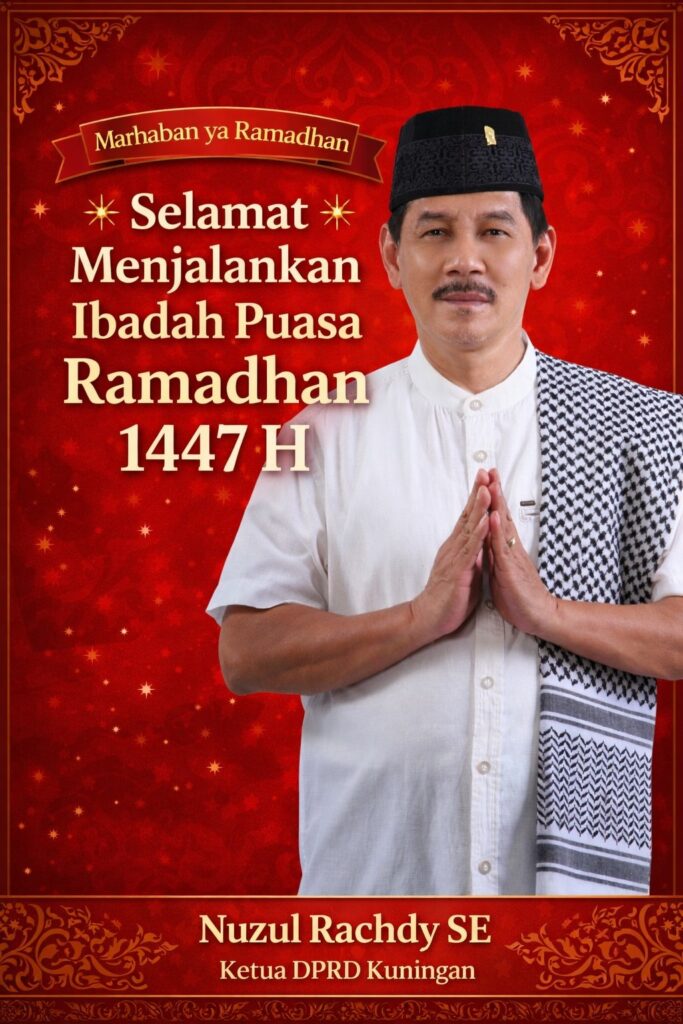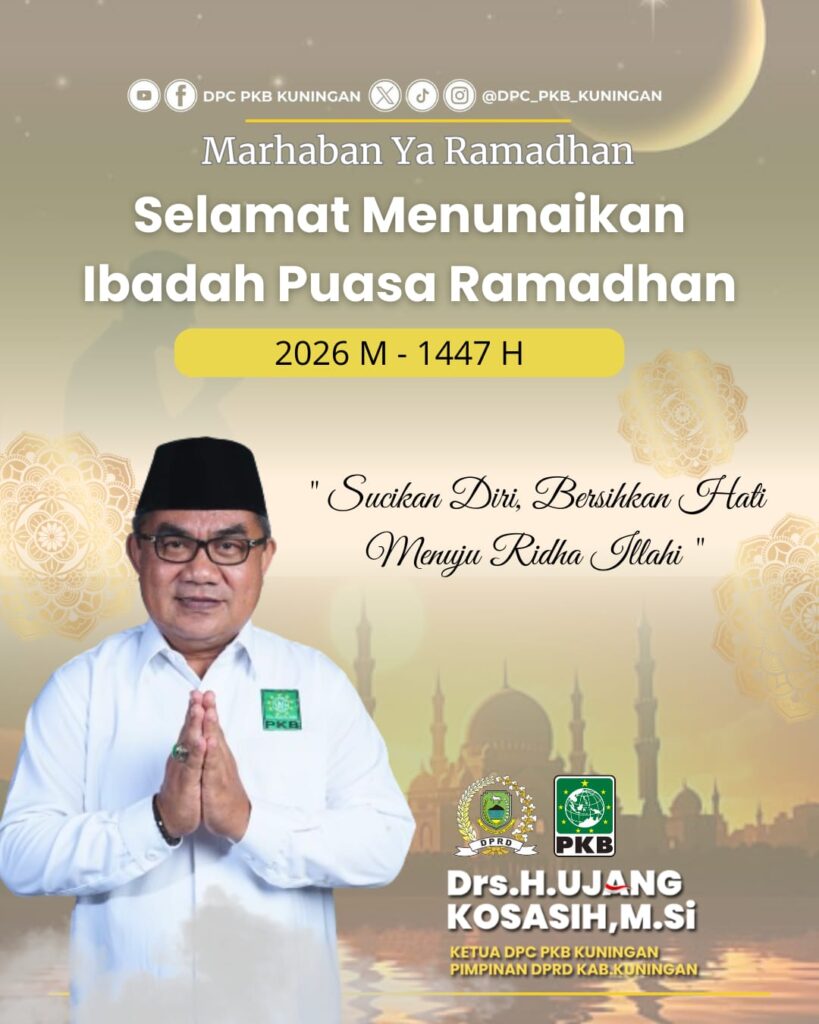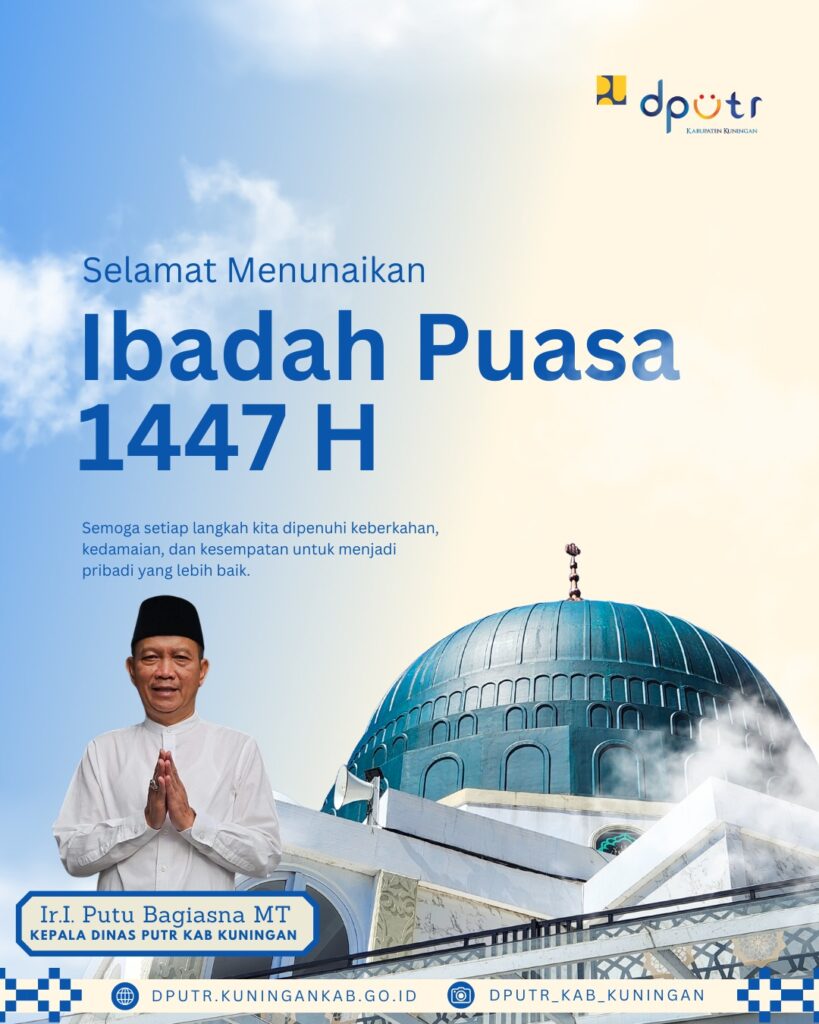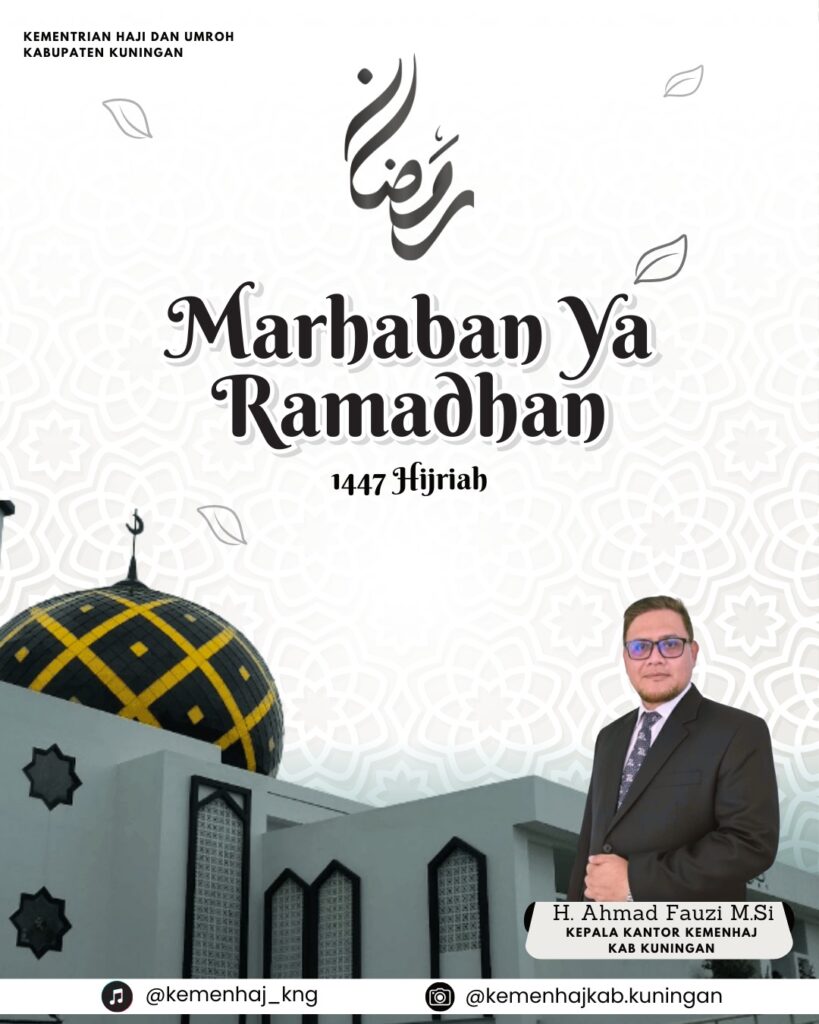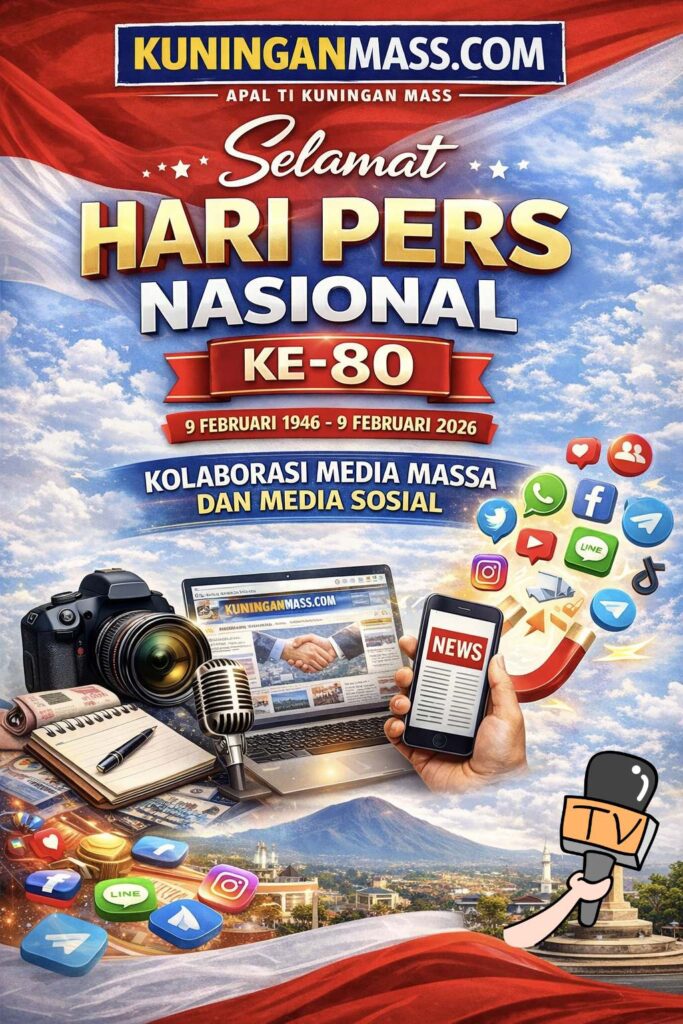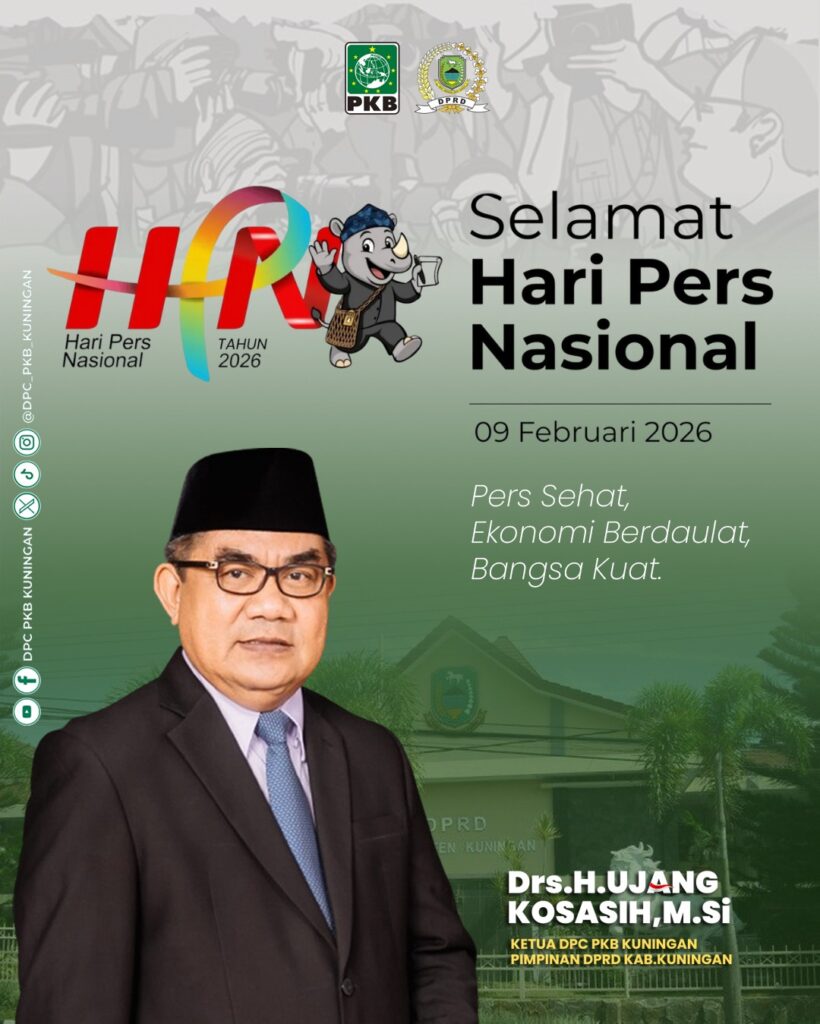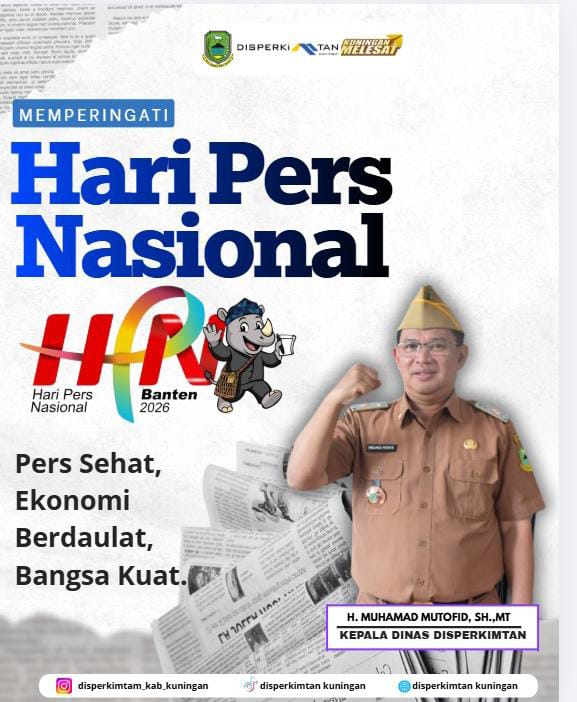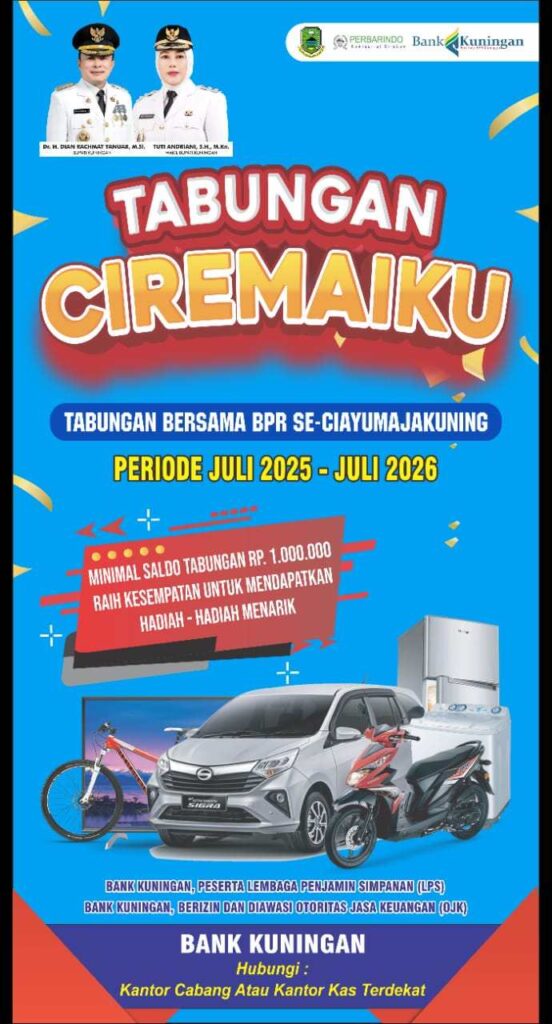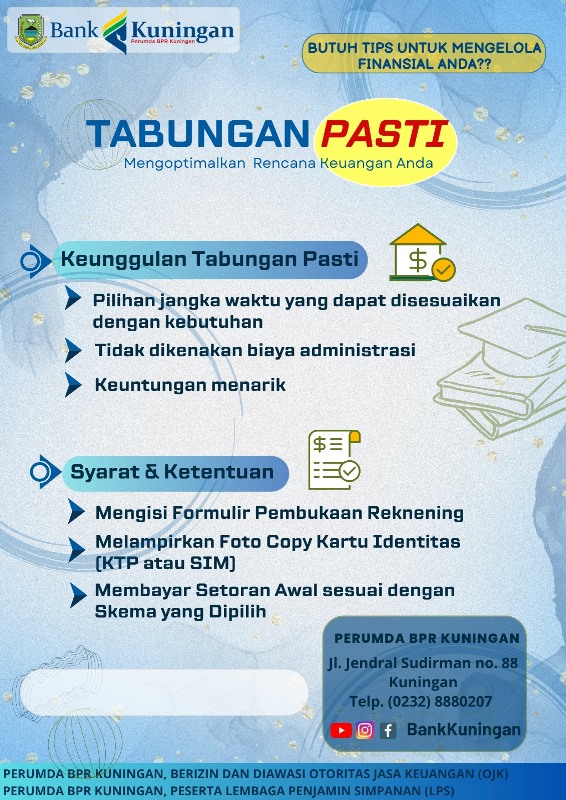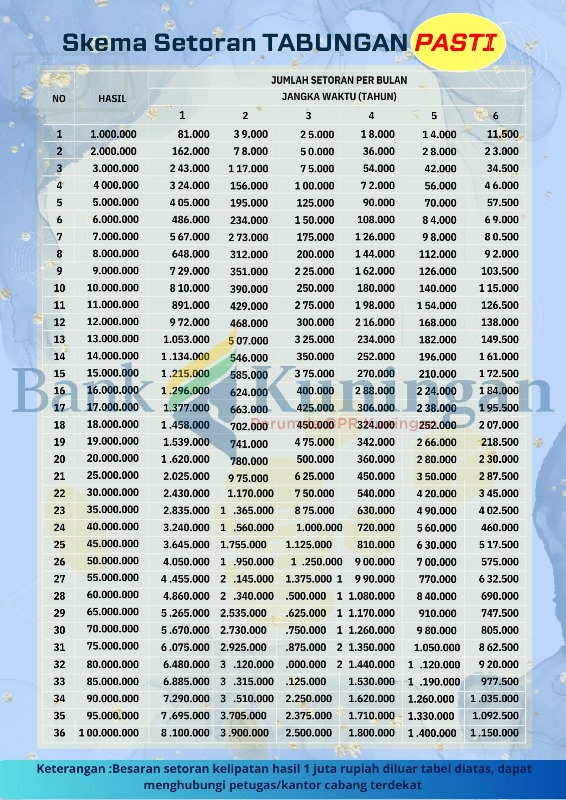Apakah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang sudah mengarah ke jebakan utang?
Pertanyaannya menggelitik karena biaya akhir proyek Whoosh terkonsolidasi di kisaran US$7,2–7,3 miliar (sekitar Rp110–113 triliun) setelah pembengkakan yang disepakati pada 2023, dari rencana awal yang lebih rendah.
Fakta kerasnya: struktur pembiayaan didominasi pinjaman dari China Development Bank (CDB), dan pemerintah kini membahas restrukturisasi dengan Beijing.
Ini belum otomatis “debt trap”, tetapi indikator risikonya nyata: biaya melonjak, tenor berpotensi dipanjangkan, dan negara ikut terpapar bila kinerja arus kas tidak sesuai rencana.
Apa indikator utama yang menunjukkan potensi jebakan utang?
Indikator pertama adalah cost overrun yang disepakati sekitar US$1,2 miliar pada Februari 2023, mengerek total biaya ke sekitar Rp113 triliun.
Kedua, ketergantungan pembiayaan pada kredit luar dengan porsi pinjaman sekitar 75% dari CDB.
Ketiga, kinerja pendapatan yang harus mengejar biaya dan kewajiban utang dalam waktu panjang. Tiga hal ini, jika tidak dibenahi, bisa mengarahkan proyek ke beban fiskal terselubung.
Di mana letak kelemahan negosiasi atau perencanaan?
Kelemahannya ada pada ekspektasi dan mitigasi risiko. Pada tahap awal, Indonesia memilih skema cepat—porsi utang tinggi, asumsi trafik optimistis—namun rangka pengaman ketika biaya membengkak dan waktu molor tidak cukup kuat.
Kini, kita menyaksikan babak negosiasi ulang yang tak terhindarkan karena proyek meleset dari timeline dan anggaran, memaksa kalkulasi ulang risiko lintas generasi.
Analogi sederhananya: kita mengambil KPR dengan uang muka kecil karena bunga terlihat ramah; ketika biaya renovasi dan pajak properti naik, cicilan yang tadinya “aman” berubah menjadi beban panjang.
Apakah struktur pembiayaan sejak awal tidak sehat atau kesalahan ada pada renegosiasi setelah cost overrun?
Jawaban jujurnya: kombinasi keduanya. Struktur awal memang rapuh—porsi utang mayoritas, kontinjensi terbatas—lalu renegosiasi pasca pembengkakan biaya mempertebal risiko, termasuk wacana perpanjangan tenor.
Di sini, arsitektur fiskal dan tata kelola proyek diuji: apakah negara mampu mengubah beban menjadi kewajiban yang terukur, atau justru menumpuk “biaya diam” yang memakan ruang APBN ke depan.
Seberapa realistis opsi pembayaran sampai 60 tahun dan wacana cicilan Rp1,2 triliun per tahun tanpa membebani APBN?
Perpanjangan hingga 60 tahun—yang diberitakan dalam konteks restrukturisasi—memang merenggangkan arus kas jangka pendek, tetapi menambah beban bunga dan ketidakpastian jangka panjang.
Angka Rp1,2 triliun per tahun terdengar kecil dibanding total APBN, namun sifatnya bukan “gratis”: jika arus kas proyek tak menutup kewajiban, lubangnya bisa berbalik ke BUMN dan pada akhirnya fiskal negara. Ini akan menjadi bom waktu bagi fiskal Indonesia. Seharusnya negosiasi bukan kepada tenor. Melainkan kepada bunga yang lebih rendah dan rencana pengembangan yang tidak membebankan APBN.
Kebijakan menjadi realistis hanya bila ditopang proyeksi pendapatan yang kredibel dan penguatan basis penerimaan non-tiket (TOD, komersial, konektivitas feeder).
Adakah model pembayaran atau restrukturisasi yang lebih ideal?
Ada beberapa opsi yang lebih adil risiko–imbalan.
Pertama, revenue-linked repayment: cicilan mengikuti kinerja pendapatan proyek, sehingga beban tidak kaku ketika trafik melemah.
Kedua, konversi sebagian utang ke ekuitas agar risiko dibagi dan insentif kreditor–operator selaras.
Ketiga, swap kurs/tingkat bunga untuk meredam volatilitas; keempat, milestone-based grace period sehingga pembayaran penuh baru berlaku setelah indikator operasi–okupansi tercapai.
Analogi yang memudahkan: seperti kontrak sewa kendaraan berbasis kilometer, bukan waktu kalender—bayar sesuai pemakaian nyata, bukan asumsi yang terlalu optimistis.
Negosiasi semacam ini masuk akal mengingat pemerintah memang tengah membuka kanal pembahasan restrukturisasi dengan pihak Tiongkok.
Langkah agar utang tidak berubah menjadi “liability trap” permanen
Pertama, audit independen menyeluruh atas struktur biaya, kontrak, dan proyeksi—dan dipublikasikan—untuk memulihkan kepercayaan.
Kedua, optimalkan pendapatan: integrasi antarmoda, tarif dinamis, dan pengembangan TOD/komersial di simpul stasiun agar porsi pemasukan non-tiket meningkat; data KCIC menunjukkan penumpang kumulatif 2025 menembus 5,1 juta hingga Oktober dan rekor harian di atas 26 ribu—basis ini harus dikapitalisasi, bukan dibiarkan sporadis.
Ketiga, tata kelola BUMN proyek diperkuat dengan target kinerja yang terukur dan mekanisme peringatan dini.
Keempat, renegosiasi berbasis kinerja dengan CDB—bukan sekadar memperpanjang tenor—agar beban fiskal jangka panjang tidak disamarkan.
Pada akhirnya, proyek ini akan diingat bukan karena kecepatannya saja, tetapi sejauh mana ia mengajar kita tentang disiplin fiskal dan keberanian memperbaiki desain kebijakan di tengah jalan.
Jangan Tutupi Masa Lalu
Whoosh tetap bisa menjadi simbol modernitas bila kita mendisiplinkan arsitektur pembiayaannya.
Data terakhir menegaskan skala biaya sekitar US$7,3 miliar, pembengkakan yang telah disepakati, dan pembicaraan restrukturisasi yang berjalan.
Di persimpangan ini, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengonversi risiko menjadi kontrak yang lebih cerdas: pembayaran yang mengikuti kinerja, pembagian risiko yang lebih seimbang, dan penggerak nilai tambah di koridor Jakarta–Bandung.
Jika tidak, perpanjangan tenor 60 tahun hanya akan menunda masalah—sebuah rel panjang menuju beban fiskal lintas generasi. Ini harus kita tolak
Sebaliknya, dengan negosiasi yang tegas dan tata kelola yang transparan, kita masih punya kesempatan mengubah cerita Whoosh dari kekhawatiran jebakan utang menjadi studi kasus reformasi pembiayaan infrastruktur yang matang.
Achmad Nur Hidayat — Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta