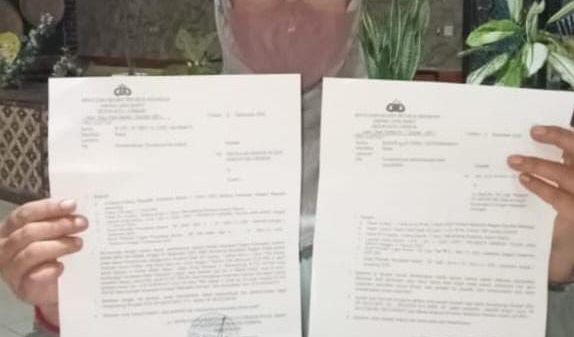KUNINGAN (MASS) – Pada Kamis, 15 Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 1.200 rektor, guru besar, dan dekan di Istana Jakarta Pusat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie, menyebut pertemuan ini sebagai momen bersejarah. Namun pertanyaannya, bersejarah untuk siapa dan untuk apa?
Dalam pertemuan tertutup yang konon tanpa dialog itu, Menkes Nek Prasetiohadi menyampaikan bahwa Presiden membahas pandangannya tentang swasembada pangan, swasembada energi, dan kemandirian bangsa, serta peran perguruan tinggi dalam mewujudkannya. Prabowo juga memberikan update kondisi geopolitik, upaya percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter nasional, dan menyoroti peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi mulai dari kualitas dosen, sarana prasarana, hingga efisiensi operasional perguruan tinggi negeri. Pemerintah, kata pejabat yang hadir, tengah mengkaji berbagai skema untuk menekan beban biaya operasional kampus agar tidak memberatkan masyarakat dan mahasiswa.
Di permukaan, semua terdengar baik. Namun di balik kemegahan pertemuan itu, muncul pertanyaan kritis yang mengganggu: apakah 1.200 akademisi bergelar tertinggi itu hanya hadir untuk mendengar, ataukah mereka benar-benar diberi ruang untuk berpikir dan berbicara?
Pengamat politik dan intelektual publik Rocky Gerung dengan tegas mempertanyakan substansi pertemuan tersebut. “Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200-an rektor dan guru besar, saya bertanya hasilnya apa? Pasti tidak ada,” ujarnya. Rocky melontarkan kritik tajam tentang nasib universitas sebagai ruang kebebasan berpikir dan nasib riset ketika dana pendidikan dialihkan untuk program makan siang bergizi. “Tidak ada profesor yang bertanya. 1.200-an guru besar zonk. Apakah mereka guru besar? Ya, titlenya besar dengan otak kecil,” kata Rocky, sebuah sindiran yang memang menyakitkan namun patut direnungkan.
Kritik serupa datang dari cendekiawan muslim Prof. Dr. Fahri Hamzah Amhar melalui tulisan berjudul “Lebih Baik Jadi Guru Kecil Tapi Berotak Besar daripada Jadi Guru Besar Berotak Kecil.” Amhar menguraikan ironi yang terjadi di negeri ini, yang tidak datang dalam bentuk kebodohan massal, tetapi justru lahir dari diamnya para cendekia. Dia menyoroti ketidakadilan yang terjadi ketika guru honorer yang puluhan tahun mengabdi dengan upah tidak layak harus kalah dalam sistem birokrasi, sementara petugas program pemerintah bisa relatif cepat diangkat menjadi PPPK dengan jalur administrasi yang jauh lebih singkat. “Bukan soal iri, ini soal keadilan nalar,” tegasnya.
Amhar kemudian mempertanyakan sunyi yang menyertai pertemuan tersebut. Bayangkan, 1.200 guru besar dipanggil presiden, 1.200 pemilik gelar akademik tertinggi, 1.200 orang yang hidupnya seharusnya ditopang oleh sains, riset, dan nalar kritis. Namun nyaris tak terdengar satu pertanyaan kritis, satu pengingat berbasis data, satu keberanian intelektual untuk berkata “maaf, ini tidak tepat.” Jika guru besar hanya menjadi ornamen legitimasi kekuasaan, maka gelar profesor tidak lagi bermakna epistemik, melainkan sekadar administratif.
Dalam analisisnya, Amhar membandingkan “guru besar” dengan “guru kecil” dalam konteks fungsi intelektual, bukan status sosial. Guru kecil, guru honorer, guru desa, guru di pinggiran, seringkali lebih jernih berpikir tentang realitas dan lebih berani bersuara. Mereka mungkin tidak punya podium nasional, tapi masih punya akal sehat. Sebaliknya, ketika seorang guru besar takut bertanya, alergi mengkritik, dan nyaman dalam diam yang aman, maka yang mengecil bukan jabatannya melainkan fungsi intelektualnya. Sejarah menunjukkan ilmuwan besar diingat bukan karena gelarnya, tetapi karena keberanian mereka melawan arus kekuasaan yang keliru.
Amhar menutup kritiknya dengan pilihan moral yang tegas: lebih baik menjadi guru kecil berotak besar yang miskin secara materi tetapi jujur secara intelektual, daripada menjadi guru besar berotak kecil yang mapan tapi bisu di hadapan ketidakadilan. “Bangsa ini tidak akan kekurangan gelar. Bangsa ini kekurangan keberanian berpikir. Dan tanpa itu, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang pintar menghitung, tetapi takut bertanya.”
Sebagai penulis yang mengamati dinamika ini, saya tidak bermaksud menghakimi niat baik pemerintah dalam mengumpulkan para akademisi. Namun saya tidak bisa menutup mata terhadap pertanyaan mendasar yang terus mengganggu: untuk apa gelar akademik tertinggi jika tidak digunakan untuk melindungi kebenaran dan keadilan? Untuk apa riset dan nalar kritis jika lumpuh di hadapan kekuasaan?
Saya percaya masih banyak guru besar yang berani berpikir kritis, sebagaimana masih banyak guru kecil yang tidak kehilangan akal sehatnya. Namun kesunyian dalam pertemuan yang konon bersejarah itu membuat saya bertanya-tanya: apakah kita sedang menyaksikan transformasi universitas dari benteng pemikiran kritis menjadi sekadar alat legitimasi kebijakan? Jika ya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan pendidikan, tetapi masa depan bangsa yang mampu berpikir jernih dan berani bertanya.
Kritik ini bukan untuk membuat siapa pun baper, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kehormatan intelektual tidak datang dari gelar atau jabatan, melainkan dari keberanian untuk berbicara ketika kebenaran sedang dipertaruhkan. Dan dalam konteks Indonesia saat ini, keberanian semacam itu bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Pertanyaan krusial yang tersisa Adalah apakah pertemuan 1.200 akademisi itu benar-benar ruang dialog intelektual, ataukah sekadar ritual kekuasaan yang membutuhkan legitimasi akademik? Dan lebih penting lagi, di mana keberanian intelektual para guru besar kita ketika bangsa ini justru sangat membutuhkannya?
Kritik ini mengingatkan pada kisah klasik Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta yang sangat populer. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berkunjung ke Madinah dan meminta Imam Malik datang ke istana untuk mengajarkan kitabnya, Imam Malik menolak dengan halus. Beliau mengatakan, “Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi,” menegaskan prinsip bahwa ilmu itu mulia dan tidak seharusnya tunduk pada penguasa demi menjaga kemurniannya. Harun ar-Rasyid akhirnya datang ke rumah Imam Malik, menunjukkan rasa hormat dan keseriusannya terhadap ilmu, sehingga Imam Malik bersedia mengajarnya.
Oleh: Sekum HMI Cabang Kuningan, Uhin