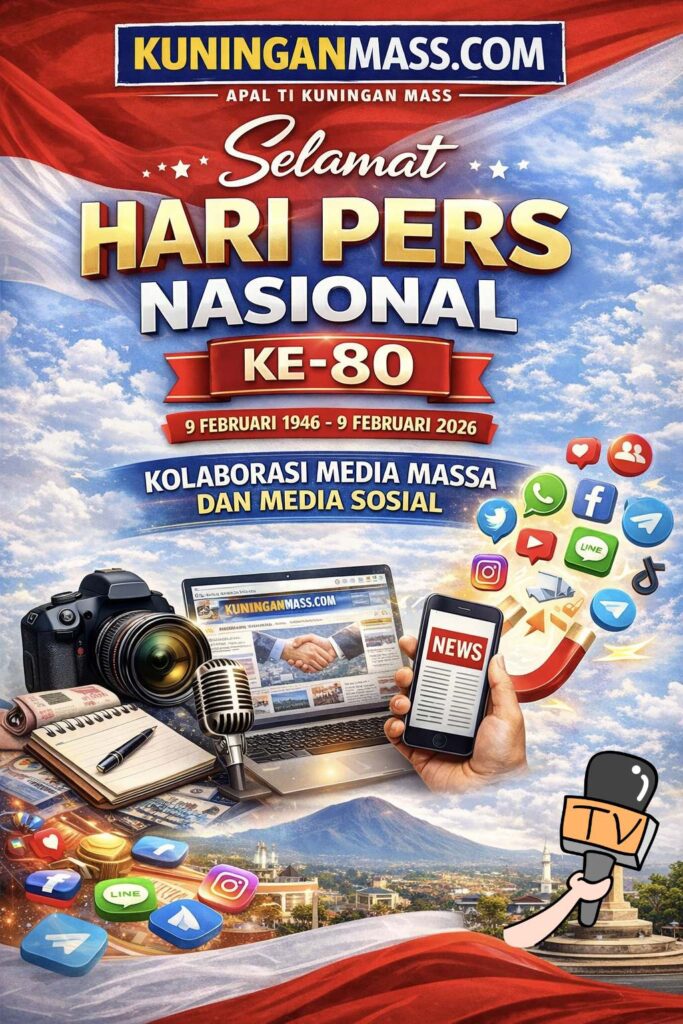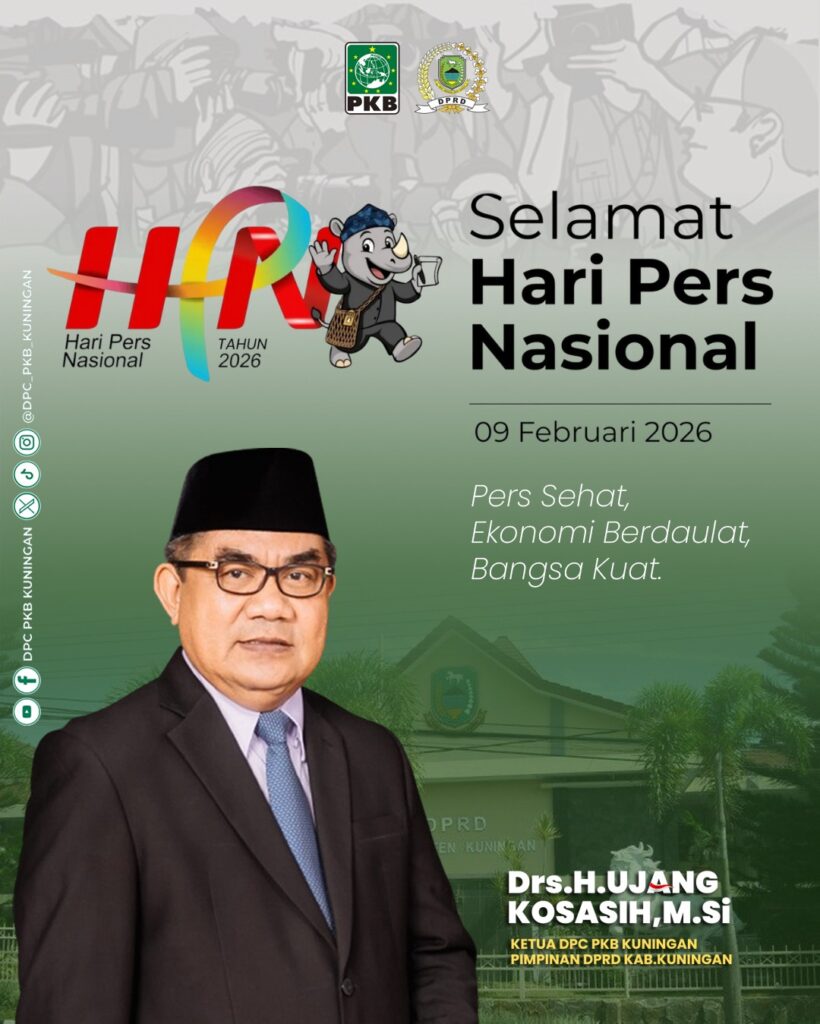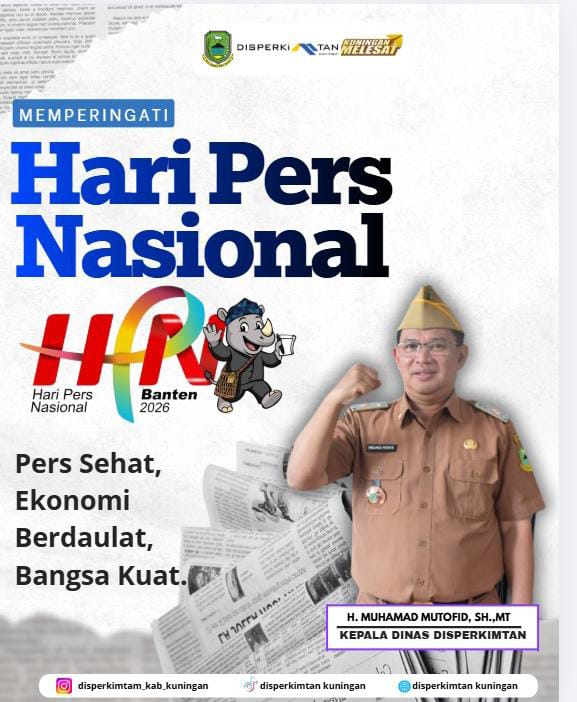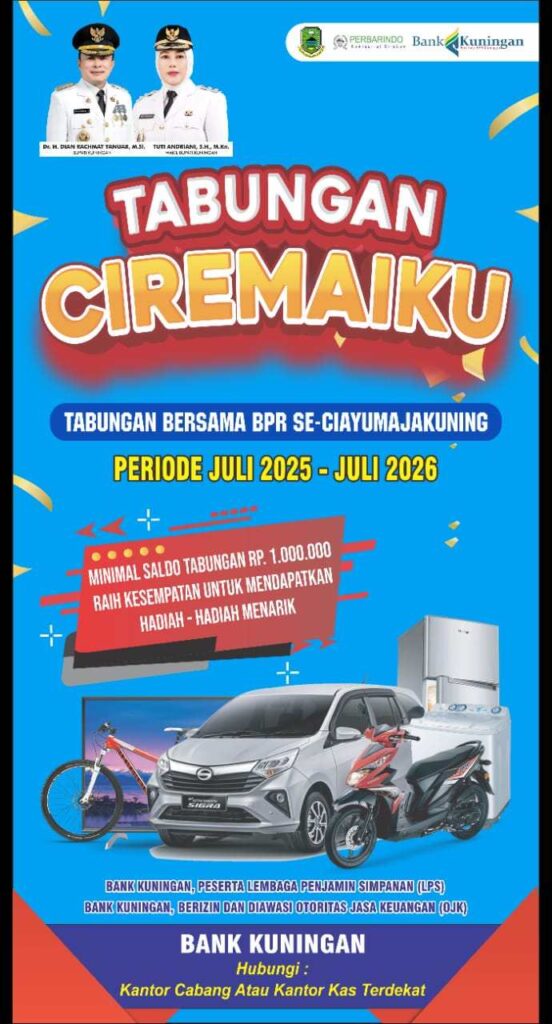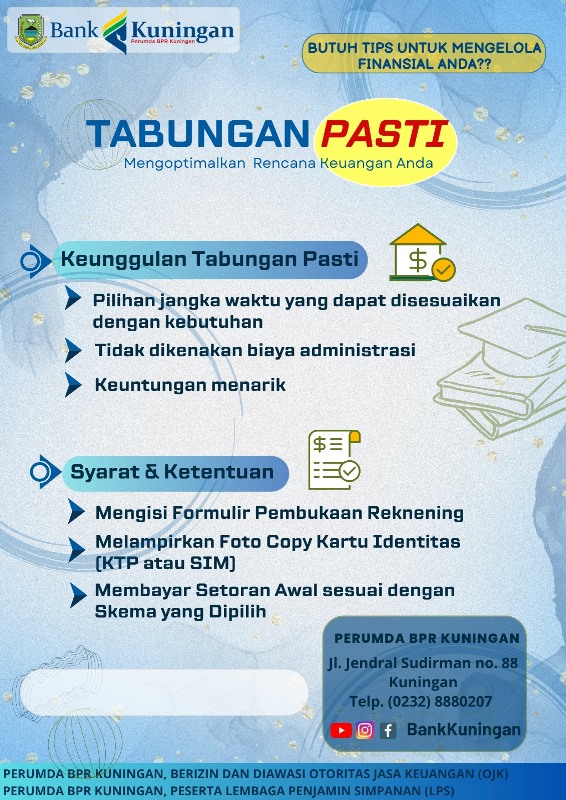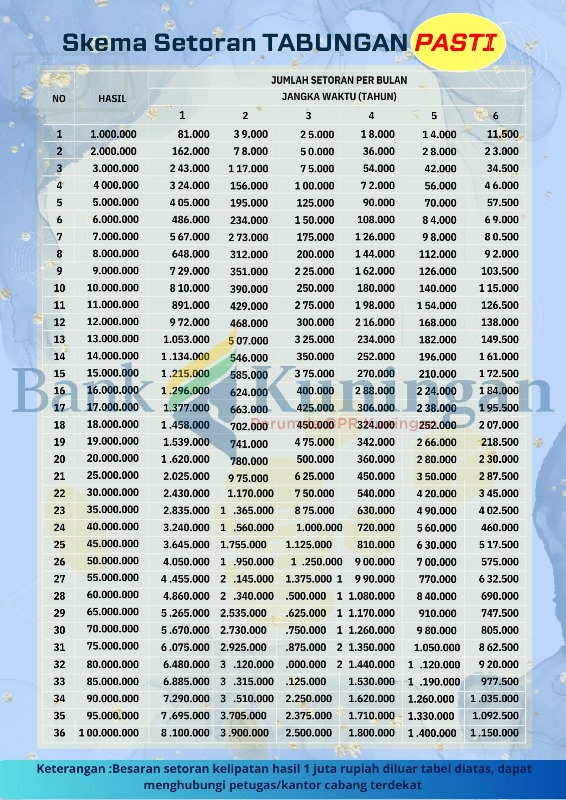KUNINGAN (MASS) – Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan kembali redenominasi rupiah—menghapus tiga nol dari nominal uang agar seribu rupiah menjadi satu rupiah baru—pertanyaan mendasarnya bukanlah “bagaimana caranya”, melainkan “untuk apa sekarang?”.
Dalam konteks ekonomi yang masih rapuh akibat tekanan daya beli, stagnasi investasi, dan pengangguran yang meningkat di beberapa sektor, redenominasi justru terasa seperti mengelupas cat dinding rumah yang retak tanpa memperbaiki fondasinya.
Masalahnya bukan pada konsep redenominasi itu sendiri.
Secara teori, penyederhanaan nominal mata uang bisa memudahkan transaksi, mempercantik citra rupiah di mata internasional, dan meningkatkan efisiensi administrasi keuangan.
Namun, persoalannya adalah timing—dan motivasi di baliknya. Apakah ini kebutuhan objektif perekonomian, atau sekadar langkah kosmetik untuk meninggalkan “legasi” politik ekonomi yang tampak elegan di atas kertas?
Ketika Simbol Menggantikan Substansi
Redenominasi seolah ingin memberi kesan “ekonomi kita sudah siap”.
Padahal, kesiapan sejati bukan diukur dari panjang pendeknya angka di mata uang, melainkan dari ketahanan ekonomi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik.
Di tengah tantangan nyata—pengangguran muda yang mencapai lebih dari 8%, daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang belum pulih penuh, serta tekanan fiskal yang meningkat akibat subsidi energi dan bansos—redenominasi bukan solusi.
Langkah ini seperti mengganti logo perusahaan saat keuangannya merugi.
Ia mungkin mengubah tampilan, tapi tidak menyentuh akar persoalan. Purbaya tampaknya ingin menciptakan simbol kemajuan—bahwa Indonesia kini “setara” dengan negara-negara yang memiliki mata uang berdenominasi kecil seperti Jepang atau Korea Selatan.
Namun, simbol tanpa substansi hanya akan menambah kebingungan publik.
Dalam psikologi kebijakan publik, kebijakan seperti ini sering disebut symbolic policy—yakni kebijakan yang lebih berorientasi pada citra daripada dampak nyata.
Kebijakan seperti ini bisa jadi populer sesaat, tetapi tidak menjawab penderitaan masyarakat yang masih bergulat dengan harga bahan pokok yang naik, lapangan kerja yang sempit, dan pelayanan publik yang belum merata.
Mengganti Baju di Tengah Badai
Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah badai. Awak kapal justru sibuk mengganti seragam mereka agar tampak rapi di foto, sementara air sudah mulai masuk ke lambung kapal.
Begitulah analogi redenominasi di tengah kondisi fiskal dan sosial ekonomi Indonesia saat ini.
Alih-alih memperkuat mesin penggerak ekonomi—yakni daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja—pemerintah justru sibuk dengan upaya kosmetik.
Memang, redenominasi tidak otomatis menyebabkan inflasi jika dilakukan hati-hati, namun biaya transisi yang harus dikeluarkan pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat tidak kecil.
Seluruh sistem keuangan, mesin kasir, pencatatan akuntansi, hingga kontrak hukum harus disesuaikan.
Di saat yang sama, tantangan riil seperti ketimpangan ekonomi, inefisiensi belanja publik, dan lemahnya kualitas layanan dasar masih belum tertangani tuntas.
Artinya, kita sedang mengalihkan energi birokrasi untuk menata simbol, bukan sistem.
Kesenjangan antara Ambisi dan Prioritas
Secara empiris, redenominasi pernah berhasil di negara-negara dengan stabilitas makro yang kuat dan kepercayaan publik tinggi—seperti Turki pada 2005 atau Korea Selatan yang melakukannya secara bertahap.
Namun, kesamaan kondisi itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.
Pertama, stabilitas rupiah saat ini masih sangat bergantung pada intervensi Bank Indonesia.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar di atas Rp16.000, sementara tekanan impor dan ekspor yang melambat membuat ruang kebijakan moneter semakin sempit.
Kedua, dari sisi psikologis, masyarakat kita masih berorientasi pada nominal besar. Seribu rupiah dianggap “uang kecil”, dan perubahan menjadi “satu rupiah baru” bisa menimbulkan kebingungan dalam harga pasar.
Pengalaman di Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan bahwa tanpa komunikasi publik dan kesiapan sistem, redenominasi justru menimbulkan inflasi ekspektasi dan kepanikan harga.
Ketiga, dari sisi manfaat ekonomi, dampak positif redenominasi terhadap pertumbuhan hampir nihil.
Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa penyederhanaan nominal mampu meningkatkan PDB, memperluas lapangan kerja, atau menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang cermat—seperti insentif APBN bagi sektor padat karya, subsidi gaji pekerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik—memiliki multiplier effect yang jauh lebih tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kemenkeu di bawah Purbaya seharusnya memusatkan perhatian pada tiga hal krusial: mengatasi pengangguran, menjaga daya beli masyarakat, dan memperbaiki kualitas layanan publik.
Pertama, Pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih sekitar 5,3%, dengan dominasi usia muda. Ini bukan hanya angka statistik, tetapi cermin ketidakmampuan ekonomi menyediakan pekerjaan bermartabat.
Kedua, Daya beli. Inflasi bahan pangan dan energi menekan konsumsi rumah tangga—kontributor 53% terhadap PDB nasional.
Ketiga, Pelayanan publik. Banyak daerah masih kekurangan layanan dasar—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kecil—yang justru memiliki dampak sosial-ekonomi jauh lebih besar dibanding redenominasi.
Dengan demikian, orientasi fiskal seharusnya bukan pada simbol moneter, tetapi pada real welfare economy—ekonomi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Gagasan Alternatif: Dorongan Fiskal sebagai Jalan Nyata
Alih-alih mengejar gengsi redenominasi, pemerintah bisa memanfaatkan momentum fiskal 2025–2026 untuk mendorong insentif produktif berbasis APBN.
Misalnya, memperluas skema subsidi upah bagi sektor UMKM, menurunkan PPh badan untuk industri padat karya, atau mengoptimalkan belanja infrastruktur kecil yang menyerap tenaga kerja lokal.
Kebijakan seperti ini memiliki efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan konsumsi domestik—yang menjadi motor utama ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, dengan reformasi pelayanan publik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja dan menekan kebocoran anggaran.
Bahkan jika motif utama redenominasi adalah “menjaga martabat rupiah”, sebenarnya martabat itu hanya bisa lahir dari kekuatan ekonomi yang nyata—bukan sekadar dari berapa nol yang tertera di uang kertas.
Simpulan: Legasi atau Ilusi?
Redenominasi rupiah, jika dipaksakan sekarang, lebih mencerminkan hasrat untuk meninggalkan legacy politik ekonomi ketimbang menjawab kebutuhan publik.
Ia seperti membangun monumen di tengah reruntuhan: indah dari jauh, tapi tidak menyelesaikan masalah.
Kebijakan ekonomi sejati adalah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya persepsi.
Dalam konteks itu, prioritas Kemenkeu seharusnya bukan pada memoles angka rupiah, tetapi pada memoles nasib rakyat.
Mengutip pepatah lama, “baju baru tidak akan membuat tubuh sehat.”
Demikian pula, redenominasi tidak akan membuat ekonomi kuat jika fondasi kesejahteraan belum kokoh.
Yang dibutuhkan rakyat bukan simbol kemajuan, tetapi keberanian negara untuk memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar kembali ke rakyat melalui lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik yang bermutu.
Redenominasi boleh jadi tampak keren di mata teknokrat, tapi bagi rakyat yang setiap hari berjuang menukar keringat dengan sesuap nasi, kebijakan semacam itu hanyalah hiasan retoris—sementara kebutuhan mendesak mereka terus menunggu di antrian panjang bantuan sosial.
Purbaya sebaiknya menulis sejarah bukan dengan menghapus tiga nol dari rupiah, melainkan dengan menambah tiga nilai dasar kebijakan publik: keberpihakan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Itulah redenominasi yang sejati—bukan redenominasi angka, tapi redenominasi makna bagi bangsa.
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta