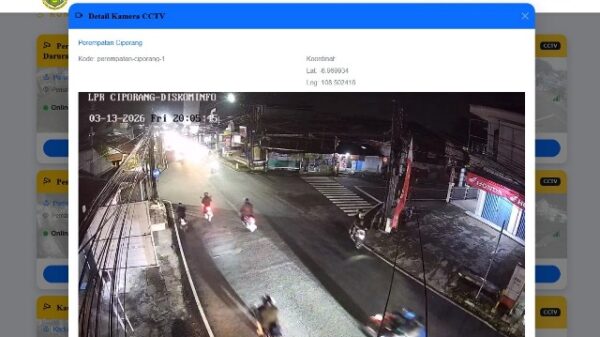KUNINGAN (MASS) – Bagi sebagian orang, harga Lembar Kerja Siswa (LKS) mungkin tampak sepele. Namun bagi banyak orang tua di Kabupaten Kuningan, LKS bukan sekadar buku tipis berisi soal-soal, melainkan tambahan beban di tengah hidup yang makin sempit. Terlebih ketika sekolah disebut gratis, tetapi biaya terus datang lewat pintu samping.
Sebagai orang tua, kami jarang bertanya banyak. Ketika sekolah menyampaikan bahwa anak perlu membeli LKS, sebagian besar dari kami langsung mengangguk. Bukan karena mampu, tetapi karena takut anak kami tertinggal pelajaran. Ketika guru mengajar dengan merujuk pada LKS, sementara anak tidak memilikinya, kami tahu siapa yang akan menanggung akibatnya, bukan sekolah, bukan penerbit, tetapi anak kami sendiri.
Kondisi ekonomi keluarga di Kuningan tidak seragam. Banyak yang hidup dari pertanian, buruh harian, pedagang kecil, atau pekerjaan informal dengan penghasilan tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, biaya pendidikan tambahan—meski terlihat kecil—sering kali berarti harus mengurangi kebutuhan lain.
Ironisnya, pengorbanan itu terjadi di tengah janji sekolah gratis yang kami percaya.
Yang membuat kami semakin bingung, LKS disebut tidak wajib, tetapi praktiknya menjadi keharusan. Anak-anak diberi tugas dari LKS, ulangan mengacu pada LKS, bahkan pembahasan di kelas pun mengikuti halaman-halaman LKS tertentu. Jika benar tidak wajib, mengapa anak yang tidak membeli selalu tertinggal?
Kami juga bertanya-tanya, mengapa bahan ajar seperti ini tidak bisa disediakan oleh sekolah. Bukankah ada dana BOS yang memang diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran? Mengapa justru orang tua yang kembali diminta menanggung biaya, sementara kami tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi pilihan yang adil?
Sebagai orang tua, kami tidak menolak pendidikan yang berkualitas. Kami ingin anak-anak kami belajar dengan baik. Namun kualitas pendidikan tidak seharusnya dibangun di atas beban ekonomi keluarga. Pendidikan yang baik justru lahir dari sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada peserta didik.
Kami tidak mempersoalkan LKS sebagai alat bantu belajar. Yang kami persoalkan adalah ketika LKS berubah menjadi kewajiban tak tertulis, tanpa alternatif, tanpa empati pada kondisi ekonomi keluarga.
Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kami—bukan tempat pertama mereka belajar tentang ketimpangan.
Harapan kami sederhana. Jika sekolah gratis memang menjadi komitmen pemerintah daerah dan sekolah, maka bebaskanlah ruang kelas dari pungutan terselubung. Sediakan bahan ajar yang bisa diakses semua anak tanpa kecuali. Jangan biarkan pendidikan di Kuningan menjadi soal siapa yang mampu membeli, dan siapa yang harus mengalah.
Karena bagi kami, orang tua di Kuningan, masa depan anak terlalu mahal untuk dibayar dengan LKS yang seharusnya tidak wajib.
Bahkan ada kekhawatiran Lebih jauh, praktik penjualan LKS membuka ruang konflik kepentingan. Ketika guru atau sekolah terlibat dalam distribusi LKS tertentu, muncul pertanyaan tentang objektivitas, transparansi, dan potensi keuntungan yang tidak semestinya. Karena seyogyanya Dunia pendidikan harus steril dari praktik semacam ini.
Sekolah gratis seharusnya dimaknai secara utuh: bebas biaya wajib, bebas pungutan terselubung, dan bebas diskriminasi akses belajar.
Jika LKS memang diperlukan, maka sekolah wajib memastikan ketersediaan bahan ajar alternatif yang gratis dan setara bagi seluruh siswa.
Jika tidak, maka istilah sekolah gratis hanya menjadi jargon kebijakan indah di dokumen tetapi timpang dalam kenyataan. Dan pada akhirnya, yang menanggung konsekuensinya bukanlah regulasi, melainkan anak-anak didik yang hak belajarnya tergerus secara perlahan.
Oleh: Agus Mauludin SE