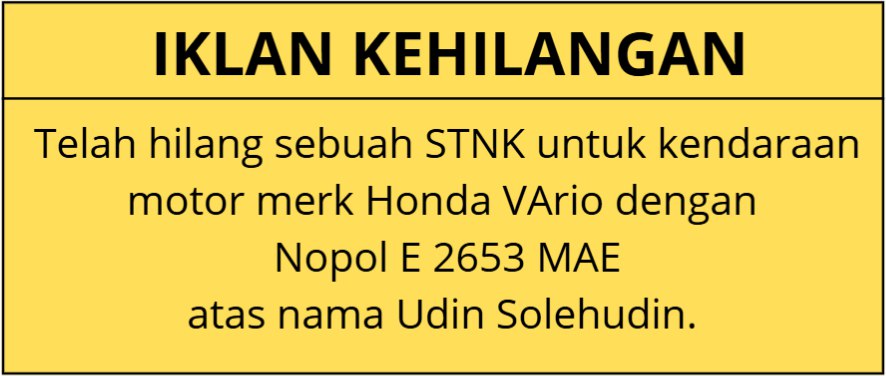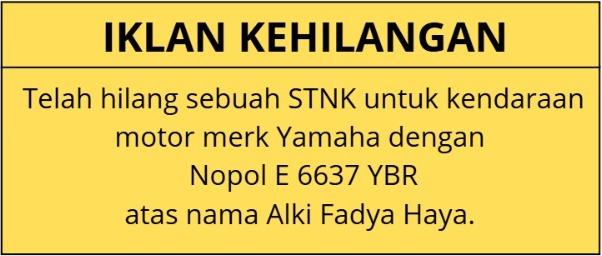KUNINGAN (MASS) – Dalam wacana pembangunan, desa kerap disebut sebagai ujung tombak. Tetapi di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Kuningan, semangat itu sering berhenti di slogan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih belum berpihak secara langsung kepada rakyat.
APBDes yang seharusnya menjadi instrumen kemandirian, kini lebih sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan birokrasi pemegang kekuasaan. Banyak pembiayaan kewenangan kabupaten diselipkan di APBDes, membuat arah pembangunan desa kehilangan makna lokalnya. Hal yang semestinya menjadi ruang aspirasi warga, justru berubah menjadi daftar belanja titipan program.
Sejatinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Begitu pula Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan berdasarkan musyawarah, kebutuhan real, dan potensi masyarakat. Namun fakta di lapangan, menukil adanya ruang kewenangan itu semakin mengecil, tergeser oleh program “turun atas nama pembinaan.”
Akibatnya, desa menjadi pelaksana tanpa daya tawar. Banyak program yang sejatinya menjadi urusan kabupaten, justru dibiayai dengan dana desa. Contohnya hal-hal yang diselipkan dalam pemberdayaan. Sementara pembinaan yang dilakukan dari tingkat kabupaten sering bersifat administratif—lebih fokus pada tumpukan laporan, bukan peningkatan kapasitas.
Apabila situasi ini dibiarkan, maka kemandirian desa hanyalah mitos administratif. Desa menjadi objek yang tergantung, bukan subjek yang berdaulat. Jean-Jacques Rousseau pernah menulis, “Manusia dilahirkan merdeka, tetapi di mana-mana ia terbelenggu.” Begitu pula nasib banyak desa, dilahirkan mandiri secara hukum, tetapi dibelenggu oleh sistem yang tidak sepenuhnya jujur.
Kemandirian yang Terikat
Ironisnya, ketika pemerintah berbicara soal “desa digital”, “desa wisata”, atau “desa mandiri,” sering kali yang sebenarnya terjadi adalah peningkatan ketergantungan baru—pada program, proyek, dan laporan. Padahal makna kemandirian bukan pada banyaknya anggaran, tetapi pada kemampuan menentukan arah berdasarkan kebutuhan warga.
Desa semestinya menjadi ruang pembelajaran politik paling jujur. Di sana, rakyat mengenal arti partisipasi dan gotong royong. Namun jika perencanaan desa hanya menjadi agenda administratif, maka nilai-nilai itu akan hilang. Musyawarah desa berubah menjadi ritual tanpa makna, hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana.
Untuk itu, pembinaan dan pengawasan perlu direposisi. Kabupaten seharusnya menjadi mitra yang memperkuat, bukan mengendalikan. Pemerintah desa harus diberi ruang untuk belajar dari praktik baik, bukan hanya ditekan dengan evaluasi formalitas.
Kemandirian Butuh Keberanian Moral dan Politik
Langkah perbaikan dapat dimulai dari penegasan batas kewenangan antara kabupaten dan desa. Program kabupaten sebaiknya tidak dibebankan ke APBDes, melainkan dibiayai oleh anggaran kabupaten sendiri. Desa perlu didorong agar berani merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat—pendidikan, ekonomi lokal, dan kesejahteraan sosial.
Kemandirian Desa Tidak Akan Terwujud Tanpa Keberanian Moral
Dibutuhkan pemimpin desa yang berpikir rasional dan berjiwa pelayan. Seorang pemimpin yang memahami, seperti kata Plato, bahwa “keadilan lahir ketika setiap orang bekerja sesuai tanggung jawab dan kodratnya.”
Kabupaten yang adil adalah kabupaten yang tidak mengambil hak desa, dan desa yang kuat adalah desa yang tidak takut berkata: “Kami tahu apa yang terbaik bagi warga kami,”
Hanya dengan itulah, APBDes akan kembali pada hakikatnya—bukan sekadar lembaran anggaran, tetapi cermin dari semangat rakyat untuk mandiri.