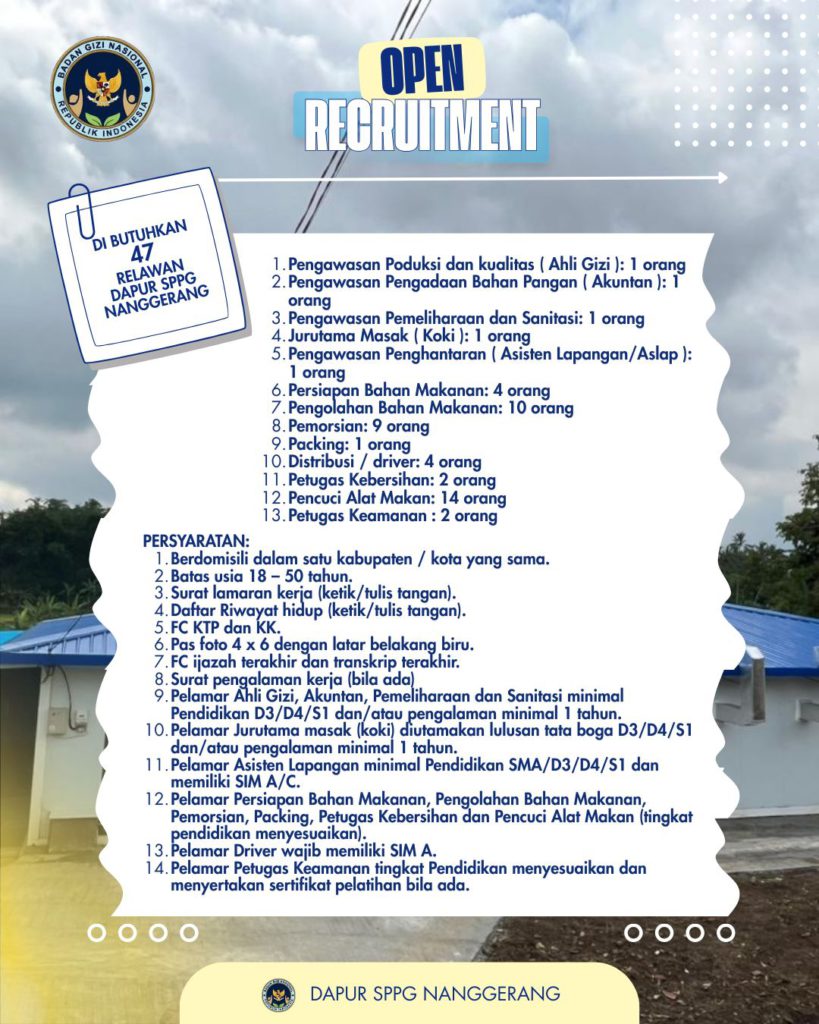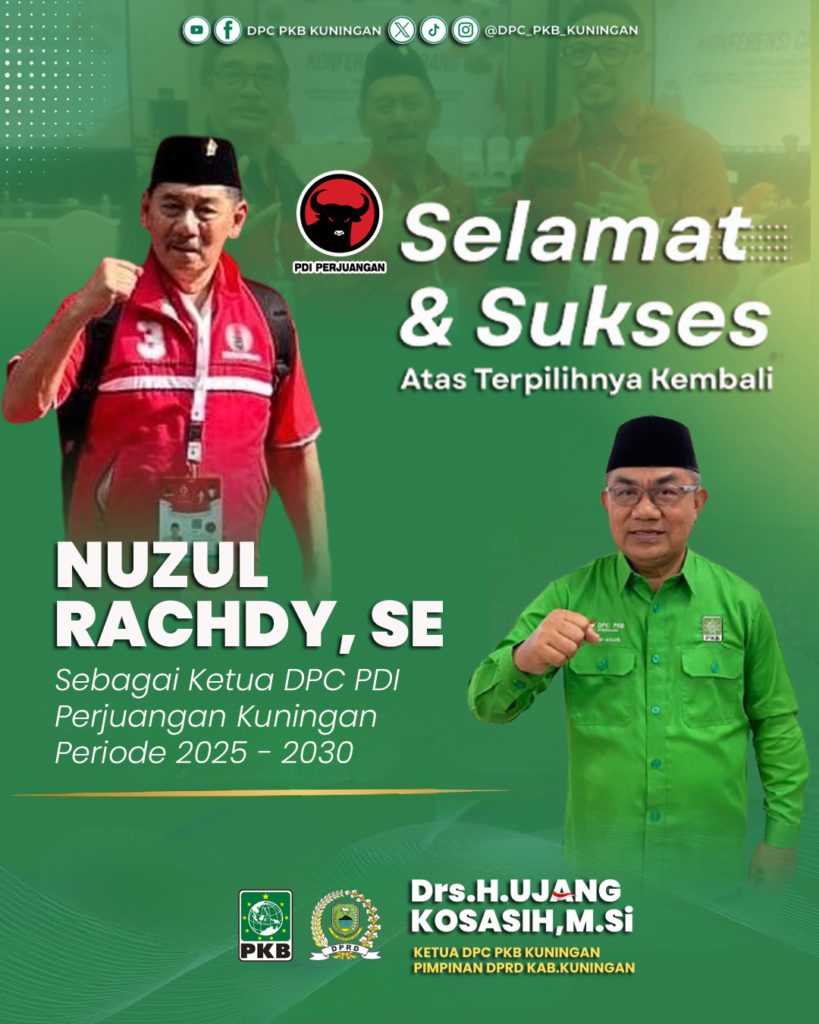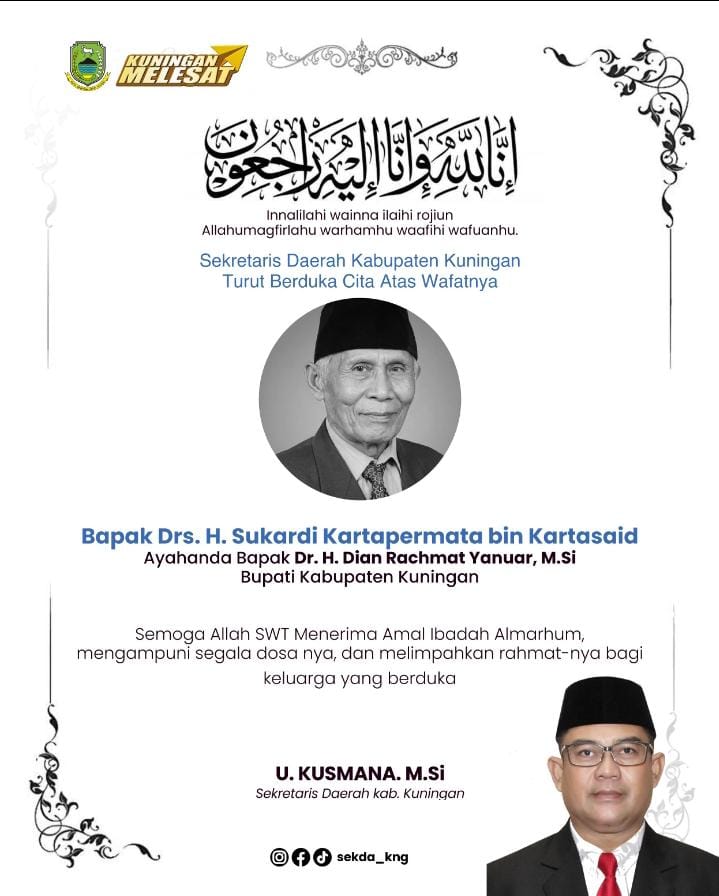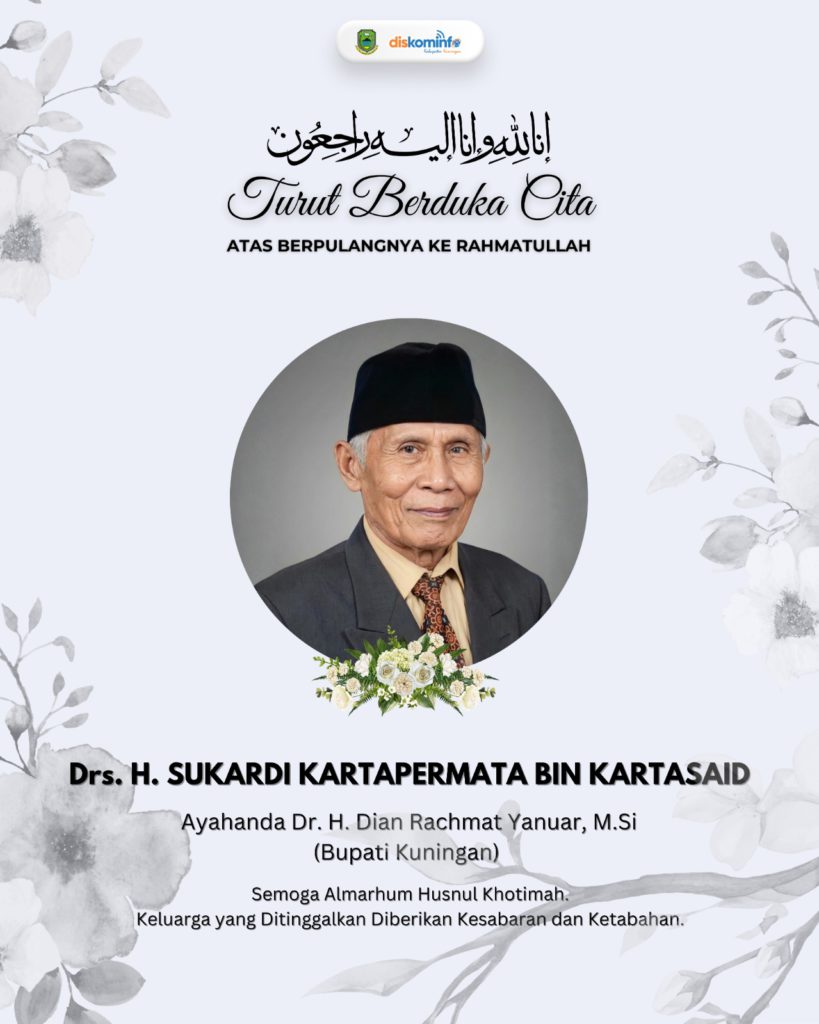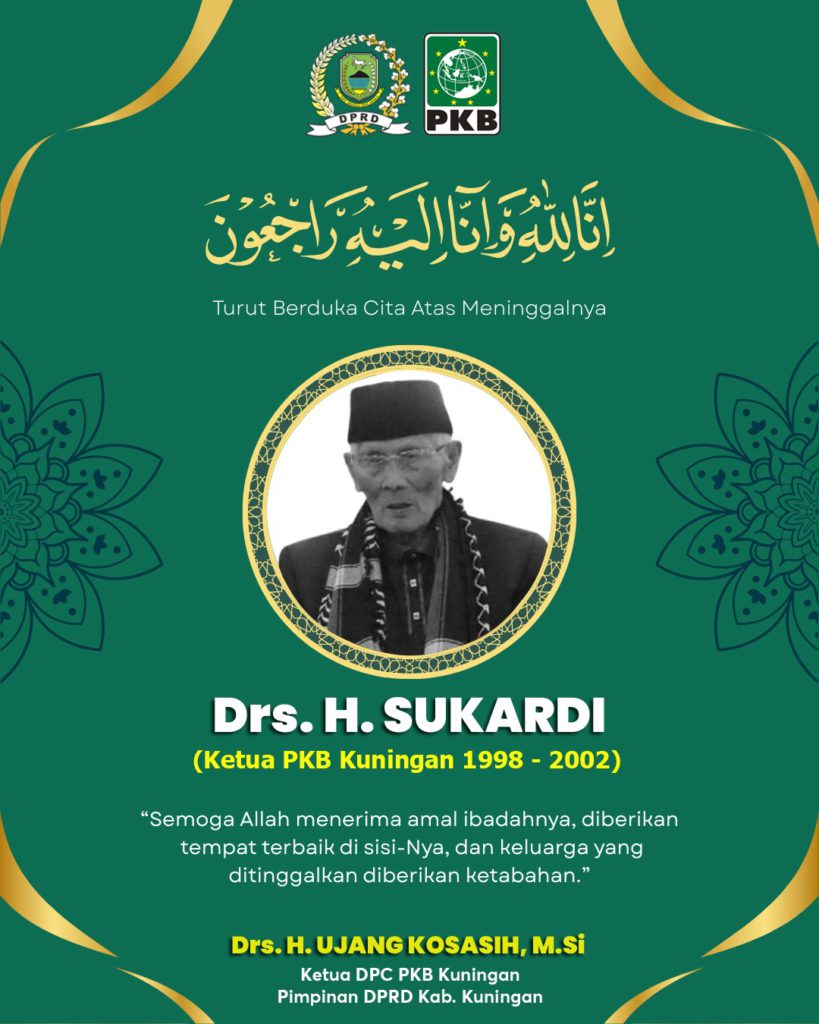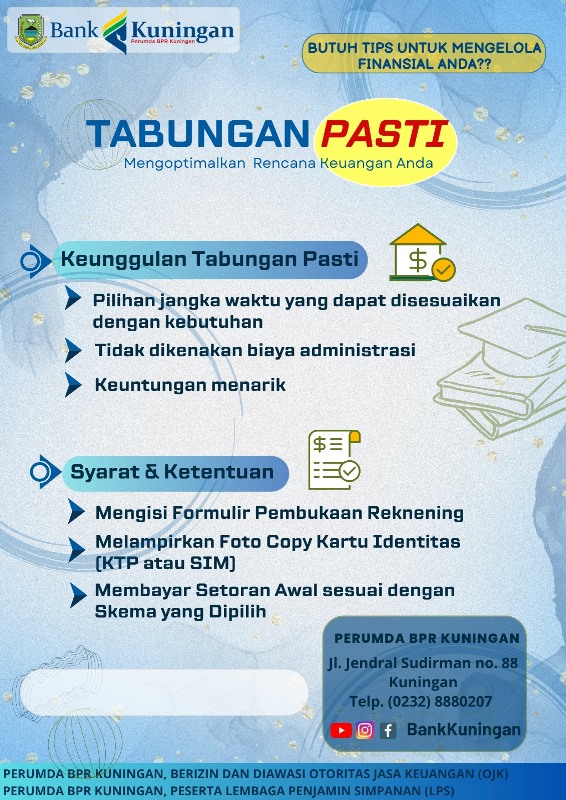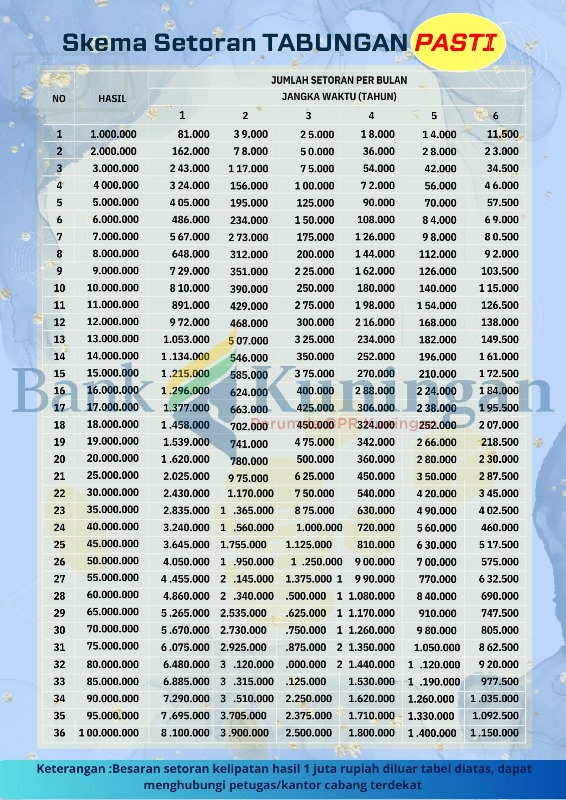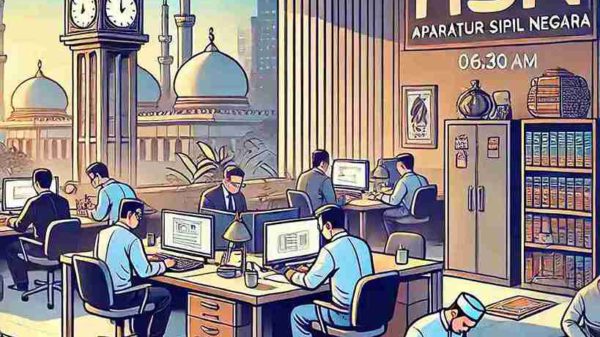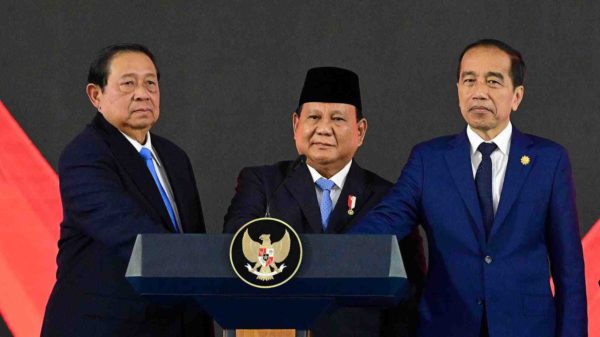KUNINGAN (MASS) – Akses jalan dari Subang ke Cilebak, memang jarang sekali baik-baik saja. Entah karena memang kontur tanah yang sering goyang, seperti yang banyak digemborkan, atau memang karena tak ada keseriusan saat menggarapnya.
Seperti itulah yang dikeluhkan warga sekitar, Nurkholik. Sekian lama jalan rusak menghubungkan Kecamatan Subang dan Kecamatan Cilebak. Bisa dilihat, sepanjang akses dari Desa Subang ke blok Puhun Cililitan.
Begitu juga lanjutan ke arah Kecamatan Cilebak. Selain tak rata, banyak jalan berlubang besar, bahkan sampai membuat genangan saat hujan.
“Butut pisan, asa teu hade-hade,” ujarnya yang juga pengguna kendaraan roda dua, Kamis (1/7/2021) siang.
Jalan yang butut, bukan hanya membuat akses tak nyaman, tapi juga tak aman dan memalukan.
Tak aman, selain karena jalannya licin, karena banyaknya lubang bisa membuat orang jatuh. Apalagi saat tergenang air, tak terlihat dimana saja titik yang dangkal dan dalam.
Tak aman juga saat malam. Selain jalannya yang ‘butut’, juga tak ada penerangan sepanjang perjalanan tersebut. Padahal, area pemukiman kadang terpisah jauh oleh ‘toang’ perkebunan.
Lalu soal memalukan, ini juga jadi hal lain. Area Kecamatan Subang dan Cilebak ini merupakan area pinggiran yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis, dan Provinsi Jawa Tengah.
Tentu memalukan, dimana kabupaten yang dicintai warganya, tidak bisa dibanggakan karena secara akses, seperti daerah tertinggal saat dibandingkan kabupaten tetangga. (Eki)